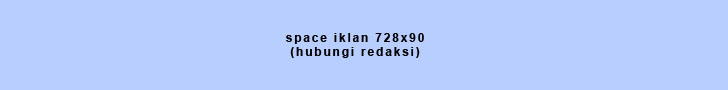Oleh
Jhon Minggus Keiya
A. Pendahuluan: Teknologi, Manusia, dan Relasi Sosial
Dalam dua dekade terakhir, kemajuan teknologi komunikasi telah merevolusi cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan mengelola kehidupan sehari-hari. Perangkat digital seperti ponsel pintar (smartphone), media sosial, dan aplikasi pesan instan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas manusia modern. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan kemudahan akses informasi, efisiensi komunikasi, dan keterhubungan lintas ruang dan waktu. Namun, di sisi lain, muncul pula berbagai dampak negatif yang tidak diantisipasi secara sosial dan psikologis, salah satunya adalah fenomena phubbing.
Istilah phubbing, singkatan dari phone snubbing, pertama kali diperkenalkan oleh Macquarie Dictionary pada tahun 2012 dalam kampanye kesadaran sosial di Australia. Phubbing merujuk pada tindakan mengabaikan orang di sekitar karena terlalu fokus menggunakan ponsel, terutama dalam situasi sosial yang seharusnya melibatkan interaksi tatap muka. Fenomena ini menjadi gejala umum di berbagai belahan dunia, dan mulai menarik perhatian para peneliti di bidang komunikasi, psikologi, dan sosiologi karena potensinya mengganggu kualitas hubungan antarpribadi.
Secara sosiologis, teknologi komunikasi telah menggeser pola relasi sosial dari interaksi langsung menjadi mediasi melalui perangkat digital. Meskipun keterhubungan secara daring meningkat, keterlibatan emosional dan kehadiran sosial secara nyata sering kali menurun. Banyak individu yang secara tidak sadar lebih terlibat dalam dunia virtual ketimbang realitas sosial yang ada di hadapan mereka. Dalam konteks ini, phubbing menjadi bentuk nyata dari alienasi sosial di era digital.
Dampaknya sangat luas. Dalam hubungan keluarga, penggunaan ponsel yang berlebihan sering mengurangi kualitas waktu bersama (quality time). Dalam hubungan romantis, phubbing dapat menyebabkan perasaan terabaikan, konflik, bahkan penurunan kepuasan dalam hubungan (Roberts & David, 2016). Di lingkungan pendidikan, mahasiswa yang terlibat dalam perilaku phubbing selama proses pembelajaran menunjukkan tingkat perhatian dan partisipasi yang rendah (Gezgin, 2017). Bahkan dalam konteks profesional, phubbing menurunkan efektivitas komunikasi tim dan membentuk kesan tidak hormat atau tidak profesional.
Oleh karena itu, fenomena phubbing tidak dapat dipandang sebagai sekadar kebiasaan buruk atau gangguan ringan. Ia adalah gejala dari perubahan sosial yang lebih dalam, yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendistorsi nilai-nilai dasar dalam komunikasi manusia: empati, perhatian, dan kehadiran.
Artikel ini akan membahas phubbing secara akademik, menggunakan pendekatan teoritis dan data empiris, untuk memahami akar persoalannya, dampaknya, serta strategi yang relevan untuk menghadapinya secara etis dan bertanggung jawab.
1. Awal Munculnya Ide Menulis Artikel Ini
Ide untuk menulis artikel ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun lalu, saat saya bersama saudari saya, Yosinta Douw, mendapatkan sebuah kesempatan istimewa. Singkat cerita, tahun lalu kami sebanyak 32 orang berkesempatan mengikuti pelatihan bahasa Inggris di Indonesia Australia Language Fondation (IALF) Bali. Dalam program tersebut, kami dibagi ke dalam dua kelas, yaitu Kelas A dan Kelas B. Saya dan saudari saya ini berada di Kelas A.
Setelah lamanya proses belajar mengajar berjalan sekitar tiga bulan lebih berlalu, dalam beberapa bulan yang tersisa selanjutnya untuk berakhirnya proses belajar mengajar ini. Satu hari, guru/tutor kami membagi kami ke dalam kelompok yang terdiri dari dua orang. Kebetulan, saya dan Yosinta menjadi satu kelompok. Pada saat itu, guru memberi kami tugas untuk membuat poster dan menentukan tema atau topik yang relevan dan penting untuk dibahas.
Kami pun mulai memutar otak mencari ide yang menarik. Diskusi kami lakukan saat jam istirahat. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, akhirnya kami menemukan sebuah ide berdasarkan fenomena yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari: kecenderungan manusia untuk terus-menerus memegang ponsel dalam berbagai situasi saat makan dan minum, sebelum tidur dan setelah bangun tidur, saat beraktivitas, bahkan ketika sedang bersama orang lain.
Dari diskusi tersebut, kami pun menetapkan tema poster kami, yaitu "Avoid Phubbing on Human". Pada hari berikutnya, kami mempresentasikan poster tersebut yang berisi penjelasan mengenai dampak negatif dan positif dari penggunaan ponsel secara berlebihan, khususnya ketika ponsel menjadi prioritas dalam interaksi sosial manusia.
2. Definisi dan Asal Usul Istilah Phubbing
Istilah phubbing merupakan akronim dari kata phone dan snubbing, yang secara harfiah berarti menolak atau mengabaikan seseorang demi ponsel. Kata ini pertama kali diperkenalkan dalam kampanye linguistik oleh Macquarie Dictionary di Australia pada tahun 2012. Kampanye tersebut bertujuan menyadarkan masyarakat akan perubahan budaya dalam interaksi sosial yang disebabkan oleh penggunaan telepon pintar secara berlebihan.
Secara konseptual, phubbing didefinisikan sebagai perilaku mengabaikan orang lain di lingkungan sosial karena seseorang lebih fokus pada perangkat seluler mereka, terutama dalam konteks komunikasi tatap muka.
Chotpitayasunondh dan Douglas (2016) menyebut phubbing sebagai bentuk gangguan dalam komunikasi interpersonal yang secara signifikan memengaruhi kualitas hubungan sosial.
Phubbing bukan hanya tindakan fisik melihat ponsel di tengah interaksi sosial, melainkan juga mencakup perilaku simbolik yang menunjukkan ketidakhadiran psikologis dan emosional. Dalam banyak kasus, pelaku phubbing mungkin tidak menyadari bahwa perilaku mereka dianggap tidak sopan atau menyakitkan bagi orang lain. Hal ini disebabkan oleh normalisasi perilaku multitasking digital dan tekanan budaya untuk terus terkoneksi secara daring (always-on culture).
Phubbing juga dapat dikategorikan sebagai gejala dari bentuk kecanduan teknologi, terutama smartphone addiction atau nomophobia (no-mobile-phone phobia), yaitu ketakutan berlebihan ketika tidak membawa atau tidak bisa mengakses ponsel. Individu yang mengalami nomophobia cenderung lebih sering melakukan phubbing, karena mereka mengalami kecemasan ketika tidak berinteraksi dengan perangkat digital (Gezgin, 2017).
Dengan kata lain, phubbing adalah simbol dari perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi secara sistemik dalam masyarakat digital. Ia mencerminkan konflik antara kehadiran virtual dan kehadiran nyata, antara keterhubungan global dan keterasingan lokal. Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam studi komunikasi kontemporer karena dampaknya terhadap relasi, empati, dan kesejahteraan sosial.
3. Perspektif Teoritis terhadap Phubbing
Untuk memahami fenomena phubbing secara komprehensif, perlu ditelaah melalui lensa-lensa teori yang menjelaskan hubungan antara teknologi, perilaku manusia, dan dinamika sosial. Tiga pendekatan teoritis utama yang relevan adalah Teori Kehadiran Sosial, Teori Ketergantungan Media, dan Psikologi Kecanduan Teknologi.
a. Teori Kehadiran Sosial (Social Presence Theory)
Teori Kehadiran Sosial, dikembangkan oleh Short, Williams, dan Christie (1976), menyatakan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh sejauh mana media memungkinkan partisipan untuk merasa “hadir” secara sosial satu sama lain. Kehadiran sosial adalah persepsi akan adanya orang lain secara nyata dalam interaksi.
Dalam konteks phubbing, ketika seseorang lebih fokus pada ponselnya dibanding pada lawan bicaranya, maka kehadiran sosial dalam interaksi itu menurun secara signifikan. Ponsel, meskipun mampu menghubungkan manusia dengan dunia luar, justru menjadi penghalang bagi keterlibatan emosional yang otentik dalam komunikasi langsung. Dampaknya, lawan bicara merasa diabaikan, tidak dihargai, atau bahkan tidak dianggap hadir secara sosial. Ketika kehadiran sosial tergerus, kualitas hubungan pun turut menurun.
b. Teori Ketergantungan Media (Media Dependency Theory)
Teori Ketergantungan Media oleh Ball-Rokeach dan DeFleur (1976) menjelaskan bahwa individu bergantung pada media untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, dan orientasi sosial. Semakin kompleks suatu masyarakat dan semakin bergantungnya individu terhadap media, maka semakin besar pula pengaruh media terhadap sikap dan perilaku mereka.
Phubbing merupakan cerminan dari bentuk ketergantungan ini. Ketika individu merasa perlu untuk terus terhubung melalui media sosial, berita daring, atau notifikasi digital, mereka menjadi rentan untuk memprioritaskan ponsel ketimbang interaksi nyata. Dalam banyak kasus, ketergantungan ini bukan lagi soal fungsional, tetapi telah bersifat psikologis dan afektif, sehingga menimbulkan konflik dengan nilai-nilai sosial dasar seperti sopan santun, empati, dan perhatian.
c. Psikologi Kecanduan Teknologi dan Nomophobia
Fenomena phubbing juga dapat dijelaskan melalui studi psikologi mengenai kecanduan teknologi. Salah satu bentuknya adalah nomophobia (no-mobile-phone phobia), yaitu rasa takut atau cemas yang berlebihan ketika seseorang tidak memiliki akses ke ponsel atau koneksi internet. Gezgin (2017) mengungkapkan bahwa individu dengan tingkat nomophobia tinggi cenderung menunjukkan perilaku phubbing lebih sering, sebagai mekanisme kompensasi untuk mengurangi kecemasan atau ketidaknyamanan sosial.
Selain itu, FOMO (Fear of Missing Out) juga turut memperparah phubbing. Ketakutan ketinggalan informasi atau interaksi online menyebabkan seseorang terus-menerus memantau ponselnya, bahkan di tengah percakapan penting. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran perhatian dari ruang sosial nyata ke dunia digital yang bersifat temporer dan sering kali dangkal secara emosional.
Dengan menggabungkan ketiga pendekatan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa phubbing bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan fenomena kompleks yang melibatkan faktor komunikasi, sosial, dan psikologis. Ia adalah produk dari perubahan struktural dalam masyarakat digital yang menuntut kesadaran kolektif dan penanganan yang terintegrasi.
4. Dampak Phubbing dalam Kehidupan Sehari-hari
Phubbing memiliki konsekuensi serius terhadap dinamika sosial dan psikologis dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Meskipun sering dianggap sebagai perilaku sepele, phubbing dapat menciptakan jarak emosional, menurunkan kualitas komunikasi, dan merusak struktur relasi sosial yang sehat. Dampaknya dapat diamati secara nyata dalam konteks keluarga, hubungan romantis, pendidikan, dan dunia kerja.
a. Phubbing dalam Hubungan Keluarga dan Romantis
Dalam keluarga, kehadiran perangkat digital yang terus-menerus digunakan saat berkumpul bersama telah menurunkan kualitas interaksi interpersonal. Aktivitas seperti makan malam bersama, yang dulu menjadi momen penting untuk berbagi cerita dan membangun kedekatan, kini sering kali terganggu oleh perhatian yang terbagi pada ponsel. Anak-anak yang menyaksikan orang tua melakukan phubbing juga cenderung meniru perilaku tersebut, sehingga menciptakan siklus komunikasi yang semakin tidak efektif dalam keluarga.
Dalam hubungan romantis, phubbing terbukti menjadi faktor pemicu konflik dan penurunan kepuasan hubungan. Studi oleh Roberts dan David (2016) menyebut fenomena ini sebagai partner phubbing, yakni ketika salah satu pasangan merasa diabaikan karena pasangannya lebih fokus pada ponsel. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa partner phubbing berkorelasi negatif dengan kepuasan hubungan, kepercayaan, dan keintiman emosional. Hal ini dapat memicu rasa tidak dihargai, kesepian, bahkan keretakan dalam hubungan.
b. Phubbing dalam Dunia Pendidikan
Di lingkungan pendidikan, phubbing mengganggu proses belajar-mengajar dan merusak suasana kelas yang interaktif. Mahasiswa yang lebih sering menggunakan ponsel saat dosen menjelaskan materi cenderung kehilangan konsentrasi dan menunjukkan performa akademik yang lebih rendah. Gezgin (2017) menyatakan bahwa perilaku ini juga berhubungan dengan menurunnya kualitas interaksi antara mahasiswa dan dosen, serta menurunnya keterlibatan kognitif dalam proses belajar.
Selain itu, mahasiswa yang melakukan phubbing secara berlebihan cenderung memiliki kemampuan sosial yang lebih rendah, karena waktu dan kesempatan untuk mengembangkan komunikasi verbal dan empati tatap muka menjadi terbatas.
c. Phubbing dalam Lingkungan Kerja dan Profesional
Di dunia kerja, phubbing dapat menciptakan kesan tidak profesional dan mengurangi produktivitas tim. Saat rapat, misalnya, karyawan yang asyik dengan ponselnya akan dianggap tidak fokus, tidak menghargai kolega, atau bahkan tidak kompeten. Hal ini dapat menurunkan rasa saling percaya dalam tim dan menghambat pengambilan keputusan secara kolektif.
Dalam interaksi dengan klien atau atasan, perilaku phubbing menunjukkan kurangnya keterlibatan dan empati, yang dapat merusak reputasi pribadi maupun institusional. Terlebih di sektor pelayanan publik atau bisnis, kesan pertama yang dibangun dari kontak mata dan kehadiran penuh sangat menentukan kualitas komunikasi dan kepuasan pelanggan.
Dari berbagai konteks tersebut, jelas bahwa phubbing bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga sistem sosial yang lebih luas. Ia melemahkan nilai-nilai dasar seperti perhatian, empati, dan rasa hormat nilai yang menjadi fondasi dalam
5. Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Sosial
Fenomena phubbing tidak hanya berdampak pada kualitas komunikasi sosial, tetapi juga berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis individu. Dalam era di mana interaksi digital semakin dominan, gangguan kesejahteraan mental akibat perilaku ini menjadi perhatian penting bagi para peneliti dan praktisi kesehatan.
a. Phubbing dan Peningkatan Rasa Kesepian
Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menjadi korban phubbing, atau mereka yang diabaikan oleh orang terdekatnya karena ponsel, lebih rentan mengalami perasaan kesepian dan isolasi sosial (Roberts & David, 2016). Ketika seseorang merasa diabaikan, kebutuhan dasar manusia akan pengakuan dan koneksi sosial tidak terpenuhi, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kesepian kronis.
Kesepian sendiri telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental, termasuk depresi, kecemasan, hingga menurunnya fungsi kognitif. Oleh karena itu, phubbing bukan sekadar gangguan komunikasi, melainkan faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi psikologis individu.
b. Gangguan Perhatian dan Stres
Penggunaan ponsel yang berlebihan dan perilaku phubbing menyebabkan fragmentasi perhatian, di mana individu sulit memfokuskan pikiran secara penuh pada satu aktivitas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan stres kronis karena otak terus-menerus menerima stimulasi yang tidak teratur dan harus berpindah-pindah fokus secara cepat.
Selain itu, Fear of Missing Out (FOMO) juga memperparah stres, terutama bagi mereka yang merasa harus selalu terhubung dengan dunia digital agar tidak kehilangan informasi penting atau interaksi sosial (Przybylski et al., 2013). Stres yang berkelanjutan berdampak negatif pada kualitas hidup, termasuk pola tidur, suasana hati, dan produktivitas.
c. Penurunan Harga Diri dan Kepuasan Hidup
Interaksi sosial yang terganggu akibat phubbing juga dapat menurunkan harga diri individu. Ketika seseorang merasa bahwa kehadirannya tidak dihargai atau diabaikan, perasaan diterima dan dihormati dalam kelompok sosial berkurang. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kepuasan hidup dan motivasi sosial (Misra et al., 2016).
Dalam jangka panjang, gangguan hubungan sosial yang berkaitan dengan phubbing dapat menimbulkan perasaan putus asa dan menarik diri dari interaksi sosial yang sehat, sehingga memperparah isolasi dan perasaan terasing.
Dengan demikian, phubbing berkontribusi pada menurunnya kesehatan mental secara signifikan dan mengancam kesejahteraan sosial. Penanganan fenomena ini harus melibatkan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya mengatur perilaku digital, tetapi juga mendukung kesehatan psikologis dan sosial masyarakat secara menyeluruh.
6. Etika Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial
Fenomena phubbing memunculkan pertanyaan mendasar mengenai etika komunikasi dalam era digital. Di satu sisi, teknologi memberi kebebasan dan kemudahan berkomunikasi; di sisi lain, penggunaan yang tidak sadar dapat mengabaikan norma-norma sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami phubbing tidak hanya sebagai perilaku individu, tetapi juga sebagai masalah etis yang menuntut tanggung jawab sosial bersama.
a. Etika dalam Interaksi Tatap Muka
Etika komunikasi tradisional mengajarkan prinsip penghormatan, perhatian penuh, dan kehadiran emosional ketika berinteraksi secara langsung. Phubbing melanggar prinsip ini karena menunjukkan kurangnya perhatian kepada orang yang sedang berbicara atau berbagi momen bersama. Dalam konteks ini, phubbing dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian sosial yang merusak rasa saling menghargai dan kepercayaan.
Kehadiran fisik tanpa kehadiran psikologis (karena fokus pada ponsel) membuat komunikasi kehilangan makna dan keaslian. Etika komunikasi modern harus menekankan pentingnya kehadiran penuh dalam interaksi, mengingat bahwa teknologi seharusnya melengkapi, bukan menggantikan, keintiman sosial.
b. Tanggung Jawab Individu dalam Penggunaan Teknologi
Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengelola penggunaan teknologi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran akan dampak phubbing harus menjadi bagian dari literasi digital, di mana pengguna belajar mengatur waktu penggunaan ponsel dan mengenali situasi yang mengharuskan fokus penuh pada interaksi tatap muka.
Disiplin diri dan empati menjadi kunci agar teknologi tidak menjadi alat yang memecah hubungan sosial, tetapi justru memperkaya komunikasi. Individu juga harus mampu menetapkan batasan, misalnya dengan menetapkan aturan bebas ponsel saat makan bersama atau rapat.
c. Peran Komunitas dan Institusi Sosial
Tanggung jawab sosial tidak hanya berada pada individu, tetapi juga komunitas dan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Pendidikan mengenai penggunaan teknologi yang etis dan sehat harus diajarkan sejak dini sebagai bagian dari kurikulum literasi digital.
Selain itu, kebijakan institusional yang mendukung budaya komunikasi efektif dapat mendorong perubahan perilaku, misalnya larangan penggunaan ponsel saat rapat atau saat jam keluarga. Media juga dapat berperan dalam kampanye kesadaran sosial yang menekankan pentingnya menghindari phubbing.
Dengan demikian, menghindari phubbing adalah tanggung jawab kolektif yang menggabungkan nilai-nilai etika komunikasi, kesadaran individu, dan dukungan sosial. Hanya dengan pendekatan holistik, kita dapat menjaga kualitas hubungan manusia di tengah derasnya arus digitalisasi.
7. Strategi Menghindari Phubbing di Era Digital
Menghindari phubbing memerlukan upaya sadar dan strategi yang efektif baik dari individu maupun lingkungan sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang sangat tergantung pada teknologi, pendekatan strategis perlu mengintegrasikan aspek psikologis, edukasi, dan kebijakan sosial agar komunikasi tatap muka tetap terjaga kualitasnya.
a. Pengelolaan Waktu dan Disiplin Digital
Salah satu strategi utama adalah pengelolaan waktu penggunaan perangkat digital. Individu disarankan untuk menetapkan batasan waktu khusus tanpa gangguan ponsel, seperti saat makan, berkumpul dengan keluarga, atau rapat kerja. Teknik seperti digital detox atau jeda digital secara berkala dapat membantu mengurangi ketergantungan berlebihan pada ponsel.
Mengaktifkan mode Do Not Disturb atau mematikan notifikasi selama waktu interaksi sosial juga bisa meningkatkan fokus dan kehadiran penuh dalam komunikasi tatap muka.
b. Meningkatkan Kesadaran dan Literasi Digital
Pendidikan literasi digital yang mengedepankan aspek etika dan tanggung jawab penggunaan teknologi sangat penting. Program pelatihan di sekolah, kampus, dan komunitas harus menanamkan kesadaran akan dampak negatif phubbing dan pentingnya menjaga kualitas hubungan sosial.
Membangun empati terhadap perasaan orang lain yang menjadi korban phubbing dapat mendorong perubahan sikap yang lebih sadar dan bertanggung jawab.
c. Penerapan Kebijakan Sosial dan Institusional
Institusi pendidikan dan dunia kerja perlu menerapkan aturan yang jelas terkait penggunaan perangkat digital selama kegiatan bersama. Misalnya, kebijakan larangan penggunaan ponsel saat pelajaran atau rapat dapat menumbuhkan budaya komunikasi efektif.
Kampanye sosial yang menyuarakan pentingnya mindful communication juga dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap orang yang tidak memegang ponsel dan meningkatkan norma sosial untuk menghindari phubbing.
d. Membangun Keterampilan Komunikasi Interpersonal
Pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif, seperti kemampuan mendengarkan aktif, komunikasi nonverbal, dan pengelolaan emosi, menjadi fondasi penting untuk meminimalisir phubbing. Ketika individu mampu menghargai interaksi tatap muka secara lebih mendalam, kecenderungan untuk mengalihkan perhatian pada ponsel akan berkurang.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, diharapkan fenomena phubbing dapat diminimalisir, dan kualitas interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat terjaga dengan baik di tengah arus digitalisasi yang semakin deras.
8. Phubbing, Smombie, dan Nomophobia: Ancaman Bagi Esensi Kemanusiaan
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa berbagai transformasi dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan ini memudahkan akses terhadap informasi dan mempercepat interaksi global. Namun di sisi lain, muncul fenomena sosial baru yang secara perlahan menggerus nilai-nilai hakiki dalam kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah phubbing, smombie, dan nomophobia.
Phubbing merujuk pada kebiasaan seseorang yang lebih memperhatikan gawai ketimbang lawan bicaranya dalam interaksi sosial. Sementara itu, smombie atau "smartphone zombie" menggambarkan individu yang berjalan atau beraktivitas dalam keadaan terfokus penuh pada layar ponsel, seolah-olah terputus dari realitas sekitar. Sedangkan nomophobia adalah istilah untuk rasa takut atau cemas berlebihan saat tidak memiliki akses ke ponsel. Fenomena-fenomena ini menunjukkan betapa teknologi, jika tidak disikapi secara bijak, dapat menimbulkan ketergantungan yang merusak relasi sosial dan spiritual manusia.
Felix Degei, dalam artikelnya di Media Papualives, menekankan bahwa kondisi ini merupakan bentuk ancaman terhadap kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual. Ketergantungan terhadap gawai telah mengganggu ruang-ruang interaksi yang seharusnya menjadi tempat pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, perhatian, dan kebersamaan.
Lebih jauh, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang seharusnya memperkaya kehidupan manusia justru telah membentuk paradigma berpikir baru yang cenderung individualistis dan mekanistik. Dalam konteks ini, teknologi bukan lagi menjadi alat bantu bagi kemanusiaan, melainkan membentuk cara hidup yang menjauhkan manusia dari esensinya sendiri.
Maka, perlu ada refleksi kritis terhadap cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Pendidikan nilai, penguatan budaya literasi digital, serta pembiasaan etika dalam penggunaan teknologi harus menjadi agenda penting dalam membangun kembali peradaban yang berpusat pada kemanusiaan. Dengan demikian, teknologi dapat kembali menjadi sarana untuk memperkuat bukan merusak esensi kehidupan sosial dan spiritual manusia.
Kesimpulan: Mengembalikan Kemanusiaan dalam Era Digital
Fenomena phubbing merupakan konsekuensi sosial yang signifikan dari perkembangan teknologi komunikasi digital yang semakin pesat. Melalui berbagai perspektif teori komunikasi dan psikologi, phubbing dipahami sebagai perilaku mengabaikan interaksi tatap muka demi perangkat seluler, yang berdampak negatif terhadap kualitas hubungan sosial, kesehatan mental, dan kesejahteraan individu.
Dampak phubbing mencakup penurunan kehadiran sosial, peningkatan rasa kesepian, stres, dan konflik dalam hubungan keluarga, pendidikan, serta dunia kerja. Oleh karena itu, pengelolaan penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab menjadi keharusan.
Melalui edukasi literasi digital, penerapan kebijakan sosial, dan pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal, masyarakat dapat menghindari phubbing dan menjaga kualitas interaksi manusia di era digital.
Referensi
- Ball-Rokeach, S. J., & DeFleur, M. L. (1976). A Dependency Model of Mass-Media Effects. Communication Research, 3(1), 3–21.
- Chotpitayasunondh, V., & Douglas, K. M. (2016). How “Phubbing” Becomes the Norm: The Antecedents and Consequences of Phone Snubbing. Computers in Human Behavior, 63, 9–18.
- Gezgin, D. M. (2017). Fear of Missing Out and Nomophobia as Predictors of Phubbing Behavior: A Study on University Students. International Journal of Educational Methodology, 3(2), 143–152.
- Misra, S., Cheng, L., Genevie, J., & Yuan, M. (2016). The iPhone Effect: The Quality of In-Person Social Interactions in the Presence of Mobile Devices. Environment and Behavior, 48(2), 275–298.
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841–1848.
- Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). My Life Has Become a Major Distraction from My Cell Phone: Partner Phubbing and Relationship Satisfaction among Romantic Partners. Computers in Human Behavior, 54, 134–141.
- Short, J., Williams, E., & Christie, B. (1976). The Social Psychology of Telecommunications. London: Wiley.
- https://www.papualives.com/phubbing-smombie-dan-nomophobia-mendegradasikan-kodrat-manusia/
(*Penulis adalah Alumnus Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, FKIP, Pendidikan Bahasa Inggris dan pengajar di SMA Negeri 1 Dogiyai sebagai guru honorer tidak tetap).